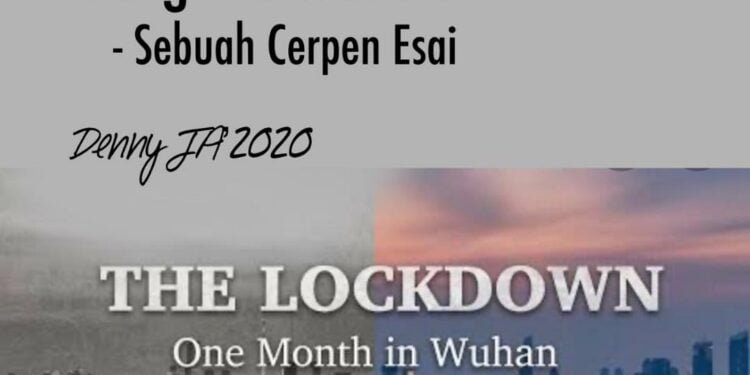Beritaenam.com — Rumah sakit itu cukup megah, tegak perkasa. Usianya sekitar 140 tahun. Ketika didirikan di tahun 1880, ia bernama Central Hospital of Wuhan. Kemudian di tahun 1893, berganti nama menjadi Chatolic Hospital.
“Yakin, Bang?,” tanya Dadi, asistenku. Ia nampak gugup sambil merapikan masker dan sarung tangan. “Bismillah saja, Di. Kita sudah sampai di sini.” Sambutku.
“Ini tempat bersejarah. Kasus pertama kali virus corona ditemukan di rumah sakit ini. Li Wenliang, (2) dokter pertama yang menemukan Virus itu bekerja di sini. Dan nara sumber kita juga ingin wawancara di sini.” Tegasku lagi.
“Kita sudah terlindungi, kan?” Tanya Didi lagi. Ia kembali menyemprot sekujur bajunya dengan disinfektan, juga menyemprot bajuku.
Kami di halaman depan rumah sakit itu. Ketika mulai masuk ke lobby, Didi kembali berguman. “Bang, bulu kudukku berdiri!” Ujarnya.
Aku diam saja sambil melangkah menuju lift. Bulu kudukku juga berdiri. Aku menyeru dalam hati, “kok bulu kudukku berdiri!”
Aku sudah keliling dunia. Semua tempat megah dan bersejarah hampir semua sudah kukunjungi. Tapi baru pertama kali aku merasakan masuk sebuah gedung, bulu kudukku berdiri.
Kuyakinkan diri. Ini buah dari persepsiku sendiri. Aku tahu, aku sedang mengunjungi tempat yang sangat bersejarah. Di rumah sakit ini, di Wuhan, bukan saja awal dari segala bencana pandemik yang kini menimpa 210 negara.
Namun di tempat ini pula, dimulai hentakan pertama. Peradaban ke depan tak akan lagi sama, walau pandemik Covid-19 selesai.
Seminggu yang lalu, draft bukuku khusus soal Li Wenliang (2) sudah selesai. Dadi asistenku, sudah pula mengedit tata bahasa. “Siap, Bang! Tinggal terbit saja.” Dadi memanggilku Abang. Ujarnya itu panggilan akrab yang ia berikan untuk senior yang ia hormati.
“Dadi!” Seruku. “Covid-19 ini peristiwa peradaban. Dalam sejarah manusia, mungkin hanya beberapa kali saja umat manusia mengalaminya.”
“Buku yang kutulis juga harus masterpiece. Peristiwa sangat besar harus pula direkam oleh karya yang sangat besar. Mustahil kita lahirkan karya agung jika semua sumbernya sekunder. Semua dari Om Google.”
“Lantas bagaimana, Bang?” Tanya Dadi. Jawabku, “kita harus pergi ke Wuhan. Kita rasakan sendiri aura kota itu. Kita selami getarannya, nafasnya. Kita saksikan kehidupan kota itu dengan mata kepala sendiri. Hanya itu cara kira mendapatkan ruh, sukma, jiwa, dan batin dari peristiwa!”
“Aku ingin hirup udara Wuhan. Minum airnya. Mandi di sana. Kencing di sana. Aku ingin kontak batin!”
“Ha!” Respon Dadi terkaget. “Mau ke Wuhan? Serius?” Dadi mulai agak takut. Sepuluh tahun sudah Dadi bekerja padaku. Ia tahu persis. Aku orang nekad. Keras kepala. Militan. Total berkarya.
“Kan Wuhan sudah tidak lagi lockdown. Hidup di sana sudah normal.” Seruku. (3)
“Kamu tak usah ikut Dadi!” Aku baru menyadari. Dadi baru saja kehilangan paman kesayangannya. Paman wafat karena corona. Untung Dadi tidak tertular. “Kamu di sini saja, tapi bantu aku untuk siapkan tiket pesawat, hotel, dan beberapa sumber untuk kudatangi.”
“Tidak bang, aku harus ikut. Kan aku sudah janji. Aku ingin terlibat dengan karya abang. Apalagi, ini ke Wuhan.” Sambut Dadi.
“Yang benar?” Tanyaku menguji. “Nanti kamu emosional di sana. Dendam karena pamanmu.” Jawab Dadi, “tidak, Bang. Saya profesional. Bisa saya pisahkan pekerjaan dengan emosi pribadi.”
Kami pun menyusun tempat di Wuhan yang akan kami kunjungi. Di samping Central Hospital of Wuhan, akan kami kunjungi pula Central Cina Normal University. 4) Di sini berkumpul kalangan terpelajar yang membela Li Wenliang, ketika ia direpresi pemerintah.
Kami juga akan mengunjungi Huanan Seafood Wholesale Market.(5) Ini tempat jual beli hewan liar. Di tempat ini, virus corona diduga berasal. Entah dari kelelawar atau Tringgiling. Lalu virus itu melompat ke tubuh manusia.
Tak lupa kami akan mengunjungi Hotel. Aku belum tahu namanya. Di hotel itu, Lin Wenliang, mengasingkan diri. Ia tak ingin virus corona yang ia derita menular pada istri dan anaknya.(6) Apalagi saat itu, istrinya hamil dua bulan.
“Jangan lupa, Di. Abangmu ini sangat suka taman. Cari taman paling bagus di Wuhan. Hari terakhir, kita duduk di sana. Kita ambil intisari semua hasil wawancara. Abangmu ingin juga rileks.” Ujarku.
Sudah 4 hari kami di Wuhan. Ini hari terakhir. Kami duduk santai di Wuhan Botanical Garden. Taman ini baru berdiri di tahun 1956. Tapi bagiku, yang penting adalah udara segar, hijau pemandangan. Lepas ke langit.
“Dadi, memberiku masukan. Apa pesan utama yang harus kita tulis soal Lin Wenliang ini?”
Jawab Dadi, “sesuai dengan keahlian abang lah. Kan abang Doktor, Ph. D di bidang Public Policy. Sisi Policynya yang kita buat headline.”
Lanjut Dadi, “Kan, Lin Wenliang dokter pertama yang menemukan Virus ini. Ia bukannya diberi penghargaan, tapi pemerintah lokal setempat malah membungkamnya. Menuduhnya menyebar kebohongan.”
“Akibatnya, respon pemerintah untuk menghalau virus sangat terlambat. Virus keburu menyebar. Bahkan ketika pemeritah me-lockdown Wuhan, banyak orang dari Wuhan sudah lebih dahulu pergi ke luar.” Sambung Dadi.
“Lihat akibatnya! Kebijakan yang buruk dari pemerintahan otoriter ini membuat dua juta populasi dunia terkena virus.” Sambung Dadi berapi-api.
“Ini jenis policy yang ‘Too Little, Too Late’. Akibatnya dunia merana. Peradaban menangis. Point ini bagus, bang. Untuk pelajaran negara lain.” Tutup Dadi.
“Ya, Dadi! Tapi jangan lupa pesan yang lebih menyentuh. Sisi tragedi dari dokter Li Wenliang. Ia dokter pertama yang menemukan virus itu. Ia dokter pertama pula yang tertular.” Responku.
“Ia akhirnya wafat dalam situasi yang tertekan. Ia adalah pahlawan karena walau dikontrol pemerintah, Ia tak henti meneliti virus itu. Ia tak henti mengobati pasien. Ia mati dalam tugas.”
“Tapi Dadi, sebelum datang ke Wuhan, aku memang niatkan menulis buku non-fiksi. Buku Public Policy. Setelah sampai di sini, terlalu banyak drama, tragedi, ironi yang kusaksikan sendiri.” Ujarku lagi.
“Aku ingin drama itu tergambar dalam karyaku. Tapi buku non-fiksi, Public Policy, tak mungkin menampungnya. Kuputuskan menuliskannya dalam novel saja.”
“Ha! Abang mau menulis novel? Tak jadi buku public policy?” Dadi kaget.
Di dalam pesewat ke Jakarta, aku banyak diam. Dadi juga diam. Ia biarkan aku berkecamuk di dalam.
Efek kunjungan ke Wuhan, tak kuduga. Air mata, ketakutan, kemarahan, harapan yang kudengar langsung begitu pekat.
Masih terbayang sahabat Li Wenliang menangis. Ia bercerita ribuan orang dipaksa hidup di rumah. Bahkan ada yang pintunya diblok dari luar agar mereka tak bisa keluar. Ramai-ramai mereka mati di sana.
Wuhan tak mungkin kulupa. Ia pun mengubahku menjadi penulis novel. ***
April 2020
Catatan
1). Catatan kaki dalam cerpen esai sangat sentral. Ia wakil dari peristiwa nyata yang diberitakan. Peristiwa nyata itu yang utama. Sementara fiksi dan dramatisasi dilakukan dalam cerpen esai ini hanya untuk membuat kisahnya lebih menyentuh.
2). Kisah Li Wenliang menjadi inspirasi cerpen esai ini. Ia dokter pertama yang menemukan virus corona. Tapi ia juga mati karena virus itu.
https://www.scmp.com/news/china/society/article/3049561/dr-li-wenliang-who-was-he-and-how-did-he-become-coronavirus-hero
3) Lockdown di Wuhan berakhir, walau warga belum sepenuhnya merasa bebas
https://m.cnnindonesia.com/internasional/20200413103404-113-492942/lockdown-berakhir-warga-wuhan-merasa-belum-nikmati-kebebasan
4) Banyak akademisi pembeli Li Wenliang berkumpul di Universitas ini:
https://en.m.wikipedia.org/wiki/Central_China_Normal_University
5) Pasar binatang liar di Wuhan diduga asal muasal Virus Corona
https://en.m.wikipedia.org/wiki/Huanan_Seafood_Wholesale_Market
6) Saat menderita terkena virus, Li Wenliang mengasingkan diri tinggal di hotel agar tidak menulari anak dan istrinya yang sedang hamil.